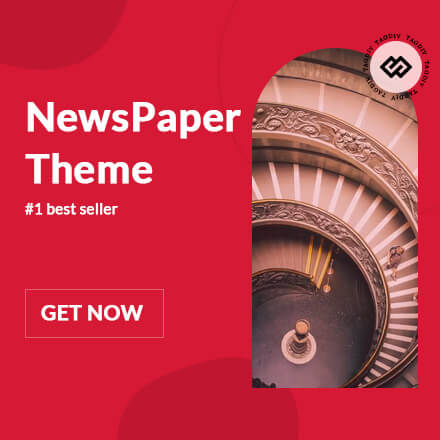Oleh: Prof. Dr. Jamhari Makruf, M.A., Ph.D.
RBN, OPINI – Mari kita bicara tentang Iran. Dalam sejarah panjangnya, Iran dahulu dikenal dengan nama Persia.
Pada tahun 1935, Reza Shah Pahlevi meminta agar nama “Iran”—yang berarti the land of Aryan—digunakan dalam komunikasi politik internasional. Sejak saat itu, Iran menjadi nama resmi negara, menggantikan Persia dalam konteks diplomatik global.
Tahun lalu (2025), saya berkunjung ke Iran, sekitar dua minggu sebelum serangan Israel terhadap tokoh militer Iran di Teheran.
Bersama peserta dari berbagai negara Muslim, kami menghadiri peringatan wafat Ayatullah Imam Khomeini di Haram Mutthohar, tempat beliau dimakamkan.
Acara tersebut dihadiri ribuan warga Iran. Dalam kesempatan itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menyampaikan pidato kenegaraan yang mengingatkan kembali pada perjuangan dan cita-cita Revolusi Islam.
Ia menekankan hak rakyat Iran untuk menentukan nasib sendiri dan memperoleh ilmu pengetahuan, termasuk kemampuan memperkaya uranium. Pidato itu disambut yel-yel keagamaan yang menggema dari para hadirin.
Iran memang sejak lama menjadi perhatian dunia. Dalam The Cambridge History of Iran (2008), dijelaskan bahwa sejak masa pra-Islam, wilayah yang kini dikenal sebagai Iran telah menjadi pusat peradaban besar.
Kekaisaran Persia yang dimulai dari Dinasti Achaemenid pada abad ke-6 SM mampu membangun kekuasaan luas dari Asia Tengah hingga Mesir dan Yunani, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia.
Setelah Achaemenid, Persia berada di bawah Dinasti Parthia dan Sassanid, yang masing-masing memiliki pengaruh signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan politik kawasan.
Pada abad ke-7 M, Islam masuk dan menaklukkan Persia. Penaklukan ini justru memberi kontribusi besar bagi peradaban Islam. Pengaruh Persia sangat kuat dalam pembentukan sastra, arsitektur, administrasi, dan filsafat Islam.
Tidak mengherankan jika banyak ilmuwan Muslim besar—seperti Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Abu Hanifah, Al-Ghazali, dan Suhrawardi—berasal dari wilayah Persia atau tumbuh dalam tradisi intelektualnya.
Pada masa Perang Dunia II, Iran kembali menjadi ajang perebutan kekuatan besar. Inggris dan Uni Soviet menaklukkan Iran karena kekhawatiran bahwa Iran cenderung mendukung Jerman.
Posisi geografis Iran yang strategis menjadikannya wilayah penting dalam jalur logistik perang. Sejak saat itu, pengaruh Barat—baik Eropa maupun Amerika Serikat—semakin kuat dalam politik Iran.
Modernisasi Iran
Iran memasuki fase modernisasi besar-besaran pada tahun 1963 melalui apa yang dikenal sebagai Revolusi Putih (White Revolution), yang dicanangkan oleh Mohammad Reza Shah Pahlevi.
Revolusi ini disebut “putih” karena dilakukan tanpa peperangan. Program tersebut mencakup industrialisasi, reformasi agraria, pemberian hak-hak perempuan, pembatasan kepemilikan lahan, serta modernisasi kota-kota besar.
Modernisasi ini membawa pertumbuhan ekonomi pesat. Harga minyak melonjak, pendapatan negara meningkat, partisipasi perempuan di ruang publik semakin nyata, dan kehidupan perkotaan menjadi lebih modern.
Namun, modernisasi tersebut juga menuai kritik tajam. Kesenjangan ekonomi melebar, urbanisasi menggerus tradisi pedesaan, pembatasan lahan memukul petani kecil, dan sekularisasi dianggap mengancam identitas keagamaan masyarakat.
Kepemimpinan Shah yang otoriter dan represif memperparah ketidakpuasan publik, hingga akhirnya meledak dalam Revolusi Iran 1979.
Revolusi Iran
Revolusi Iran yang berlangsung antara 1978–1979 mengejutkan dunia. Charles Kurzman menyebut runtuhnya kekuasaan Shah sebagai sesuatu yang unthinkable.
Rezim Shah sangat kuat, didukung militer dan Amerika Serikat. Namun, gelombang demonstrasi massal melawan otoritarianisme, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat terus membesar.
Modernisasi yang menyingkirkan peran agama memicu perlawanan ulama Syiah. Iran adalah pusat ajaran Syiah dunia, tempat pembelajaran dan ritual besar seperti Asyura dan Arbain.
Ziarah Arbain—berjalan kaki dari Najaf ke Karbala sejauh sekitar 80 kilometer—diikuti jutaan orang, bahkan diperkirakan melebihi jumlah jamaah haji.
Salah satu pilar utama ajaran Syiah adalah konsep Imamah. Dalam tradisi ini, Imam bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin sosial-politik yang dianggap maksum.
Konsep ini membangun loyalitas, solidaritas, dan ketaatan yang sangat kuat di kalangan pengikut Syiah, menjadikannya kekuatan sosial-politik yang signifikan.
Kelompok intelektual seperti Ali Shariati serta kelompok sosialis kiri juga mengkritik modernisasi yang hanya menguntungkan elit kerajaan. Kesenjangan sosial melebar, korupsi merajalela. Kelompok seperti Tudeh dan Mujahidin-e Khalq mengorganisasi gerakan bawah tanah.
Gabungan ulama Syiah, intelektual, dan gerakan kiri inilah yang akhirnya menjatuhkan Shah pada 1979.
Pasca-revolusi, Iran membentuk Republik Islam dengan konsep Wilayatul Faqih, yaitu kepemimpinan politik dan agama berada di tangan ulama tertinggi.
Konsep ini memicu perdebatan. Sebagian mengusulkan kepemimpinan kolektif ulama untuk mencegah lahirnya otoritarianisme baru. Namun, akhirnya otoritas tertinggi dipegang satu figur.
Perbedaan pandangan ini menyebabkan kelompok sosialis dan nasionalis tersingkir dari pemerintahan. Iran kemudian berkembang menjadi negara teokratis Syiah.
Dominasi ini menimbulkan ketegangan regional, terutama dengan negara-negara Sunni. Kerusuhan haji 1987 di Mekkah memperdalam luka sektarian dan geopolitik.
Revolusi Iran dianggap kemenangan Islam oleh sebagian pihak, tetapi dipersepsi sebagai kemenangan Syiah oleh yang lain. Sejak saat itu, berbagai negara mendukung upaya menahan pengaruh Iran.
Negara-negara monarki di kawasan juga merasa terancam dan mencari perlindungan keamanan ke kekuatan eksternal.
Persimpangan Masa Depan
Iran adalah negeri dengan warisan peradaban panjang, keragaman budaya yang kaya, dan sumber daya alam yang melimpah.
Minyak dan gas menempatkannya sebagai salah satu pemain penting energi dunia, sementara cadangan uranium, tembaga, besi, dan emas memperkuat posisi strategisnya dalam peta geopolitik global.
Produk pertanian bernilai tinggi seperti safron, pistachio, kurma, dan kaviar menegaskan bahwa Iran bukan hanya negeri energi, tetapi juga negeri budaya dan pengetahuan.
Letak geografisnya yang berada di simpul Asia Barat, Asia Tengah, dan jalur perdagangan dunia membuat Iran hampir mustahil diabaikan oleh kepentingan global.
Di sisi lain, kekuatan komunitas Syiah yang solid menjadi fondasi sosial-politik utama negara ini. Loyalitas pada konsep Imamah dan kepemimpinan religius menjadikan Iran memiliki bargaining power yang signifikan, baik di dalam negeri maupun di kawasan.
Sulit membayangkan perubahan besar di Iran tanpa keterlibatan kepemimpinan Syiah, karena di sanalah legitimasi moral dan politik bertumpu.
Demonstrasi besar yang kerap terjadi menunjukkan bahwa dukungan atau penolakan masyarakat Syiah dapat menentukan arah stabilitas nasional.
Tantangan ke depan terletak pada bagaimana Iran, dengan sistem Wilayatul Faqih dan dukungan sosial yang kuat, mampu membangun kemakmuran dan kedamaian yang berkelanjutan.
Sanksi ekonomi memang membatasi ruang gerak, tetapi capaian Iran dalam bidang kesehatan, teknologi, pertanian, dan bahkan sains strategis menunjukkan daya tahan yang tidak kecil.
Namun konflik eksternal yang terus berulang berisiko menguras energi bangsa dan menunda agenda kesejahteraan. Pada saat yang sama, dunia internasional juga dituntut bersikap lebih adil dan konsisten dalam menyikapi Iran sebagai bagian dari tatanan global.
Pertanyaannya, akankah Iran mampu mengubah kekuatan ideologi dan sumber dayanya menjadi jalan menuju perdamaian dan kemakmuran, atau justru terus terjebak dalam pusaran konflik yang tak kunjung usai?