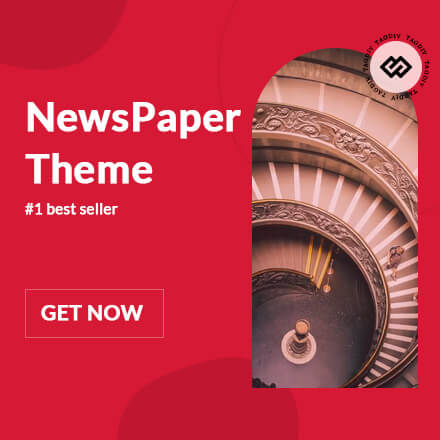Oleh: Prof. Jamhari Makruf, Ph.D.
RBN, JAKARTA – Arnold Van Gennep, seorang antropolog Prancis, adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah rites de passage, yaitu ritual yang dilakukan untuk menandai masa-masa peralihan dalam kehidupan manusia, baik dari sisi sosial, politik, maupun psikologis.
Melalui penelitiannya, Van Gennep menegaskan bahwa di mana pun berada, setiap masyarakat memiliki tradisi rites de passage.
Masa peralihan tersebut antara lain terjadi saat kelahiran, memasuki usia dewasa, pernikahan, kehamilan pada fase tertentu, hingga kematian, serta berbagai momen penting lainnya.
Periode peralihan ini sering kali menimbulkan rasa cemas, gamang, ketidakpastian, suka dan duka yang beraduk, bahkan perasaan terasing dan terpinggirkan oleh masa depan yang belum jelas.
Karena itu, ritual peralihan dilakukan sebagai bentuk dukungan spiritual untuk menghadapi “dunia baru”—situasi yang belum pasti dan kerap memunculkan kegelisahan batin.
Jika pergantian tahun kita maknai sebagai sebuah “masa peralihan” karena perubahan waktu, maka perayaan akhir dan awal tahun sesungguhnya sangat dekat dengan konsep rites de passage yang diperkenalkan Arnold van Gennep.
Pergantian tahun menjadi momen transisi—titik balik ketika manusia, secara personal maupun kolektif, meninggalkan masa lalu dan bersiap menyambut masa depan.
Beragam tradisi seperti doa bersama, refleksi diri, hingga pesta rakyat dilakukan untuk meredakan kecemasan dan ketidakpastian yang menyertai perubahan tersebut.
Melalui ritual-ritual ini, masyarakat menanamkan harapan agar tahun yang akan datang membawa kebaikan, keberuntungan, dan kehidupan yang lebih harmonis.
Perayaan pergantian tahun pun berfungsi mempererat relasi sosial dan memperkuat solidaritas bersama, sehingga ia bukan sekadar ajang pesta, melainkan juga wahana spiritual dan sosial yang penting.
Tradisi Merayakan Tahun Baru
Rites de Passage akhir dan awal tahun baru dirayakan dengan berbagai tradisi unik di seluruh Nusantara.
Setiap daerah memiliki cara khas dalam menyambut pergantian tahun, mulai dari ritual keagamaan, doa bersama, hingga pesta rakyat.
Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol harapan baru, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan sosial.
Dalam tradisi Keraton Yogyakarta dan Surakarta, peringatan tahun baru Jawa yang jatuh pada 1 Suro—bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Islam Hijriah—dirayakan secara sakral dengan rangkaian ritual penuh makna.
Di Yogyakarta, perayaan diawali dengan ritual Jamasan Pusaka, yaitu pembersihan pusaka-pusaka kerajaan oleh para abdi dalem.Ritual ini melambangkan penyucian diri dan pembaruan semangat.
Selanjutnya, keluarga kerajaan dan abdi dalem melakukan ziarah ke makam leluhur di Imogiri sebagai bentuk penghormatan dan permohonan berkah.
Tradisi khas lainnya adalah Labuhan, yaitu upacara persembahan sesaji di tempat-tempat keramat seperti Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, dan Gunung Lawu. Dalam Labuhan Pantai Selatan, sesaji dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul, sosok penjaga gaib pantai selatan.
Prosesi ini dimaknai sebagai upaya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Pada malam 1 Suro, keluarga Keraton bersama masyarakat melakukan tradisi Mubeng Beteng, mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta dalam keheningan, biasanya setelah doa bersama di masjid.
Di Surakarta, perayaan 1 Suro ditandai dengan Kirab Kebo Bule. Kerbau berbulu putih yang dianggap keramat ini diarak mengelilingi keraton.
Masyarakat percaya bahwa menyentuh kebo bule, bahkan mengambil kotorannya, membawa keberkahan. Kotoran tersebut kerap dibawa pulang untuk dicampur pupuk demi menyuburkan tanaman.
Masyarakat Tionghoa di Indonesia juga merayakan Tahun Baru Imlek dengan tradisi khas seperti pemberian angpao dan pertunjukan barongsai. Barongsai dipercaya sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, dan kebijaksanaan.
Sosok singa dalam barongsai melambangkan harapan akan keberanian dan keberuntungan di tahun yang baru.
Perayaan tahun baru—baik yang dijalani secara khidmat melalui doa maupun dirayakan dengan kemeriahan musik dan kembang api—pada dasarnya adalah momen kebersamaan.
Mengutip Émile Durkheim, collective effervescence atau kegembiraan bersama merupakan prasyarat penting bagi lahirnya solidaritas sosial. Tanpa pengalaman kebahagiaan kolektif, solidaritas sulit tumbuh.
Tahun baru adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan.
Ia ibarat lonceng penanda dalam lomba lari jarak jauh, mengajak kita berhenti sejenak untuk berefleksi: apa yang telah dicapai, janji apa yang terpenuhi, dan apa yang perlu diperbaiki.
Karena itu, perayaan tahun baru dapat dipahami sebagai cultural theatre untuk memperkuat tatanan dan solidaritas sosial.
Tidak mengherankan jika perayaan tahun baru 2026 dihimbau dilakukan tanpa kembang api sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Sumatra yang tertimpa musibah, sebagaimana perayaan tahun baru 2005 yang dijadikan ajang empati bagi korban tsunami Aceh.
Yang terpenting, perayaan tahun baru menumbuhkan kepercayaan bersama bahwa masa depan tetap terbuka dan layak diperjuangkan.
George Bernard Shaw pernah berkata, “The optimist invents the aeroplane, the pessimist invents the parachute.” Keduanya, optimisme dan pesimisme, sama-sama melahirkan karya. Manusia mungkin tidak mampu memastikan hasil, tetapi tetap bisa terus berkarya. Selamat tahun baru.