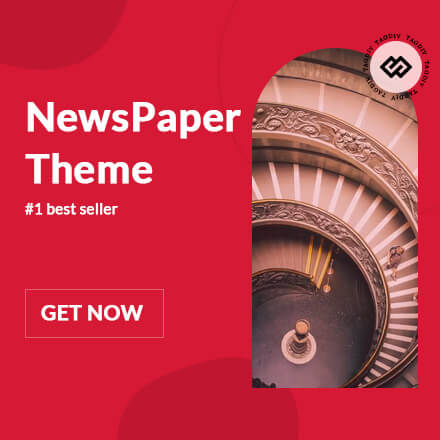Oleh: Prof. Jamhari Makruf, Ph.D
RBN, OPINI – Ibn Khaldun—yang bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami—menulis karya monumentalnya Muqaddimah (Prolegomena) pada tahun 1377.
Muqaddimah merupakan pengantar bagi karya utamanya, Kitab al-‘Ibar, yang membahas sejarah peradaban Arab, Berber, dan berbagai bangsa lain.
Para ilmuwan sosial modern menilai Muqaddimah sebagai karya perintis dalam bidang sosiologi, demografi, historiografi, dan teori perubahan peradaban.Albert Hourani, sejarawan terkemuka dunia Arab, menyebut bahwa Ibn Khaldun berhasil mengungkap “inner laws” atau hukum-hukum batin yang menggerakkan masyarakat.
Pemikiran Ibn Khaldun lahir dari pengamatannya yang tajam terhadap dinamika sejarah. Ia hidup pada masa ketika dunia mengalami perubahan besar: runtuhnya Byzantium, bangkitnya Kesultanan Turki Usmani, jatuhnya Andalusia Muslim, serta kembalinya kekuasaan Kristen Eropa atas wilayah tersebut.
Kota-kota lama kehilangan pengaruhnya, sementara pusat-pusat peradaban baru muncul.
Dari pengalaman sejarah itu, Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa peradaban tidak bersifat statis. Ia bergerak dalam siklus: lahir, tumbuh, mencapai kejayaan, kemudian menurun, dan akhirnya runtuh.
Gagasan Ibn Khaldun memberi pengaruh luas bagi pemikir modern. Albert Hourani dalam A History of the Arab Peoples menjadikan konsep ‘ashabiyah (solidaritas sosial) sebagai kunci memahami sejarah Arab.Arnold Toynbee, melalui A Study of History, mengembangkan teori tantangan dan respons yang sejalan dengan siklus peradaban Ibn Khaldun.
Ernest Gellner, dalam Saints of the Atlas, menggunakan kerangka Ibn Khaldun untuk menjelaskan relasi kekuasaan dan struktur sosial masyarakat Atlas di Maroko.
Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun tidak hanya relevan bagi dunia Islam, tetapi juga menjadi fondasi teori sosial global.Apa yang ditulis Ibn Khaldun dalam Muqaddimah merupakan refleksi atas realitas sosial masyarakat Arab-Berber di Afrika Utara dan Andalusia.
Ia menemukan bahwa usia efektif sebuah peradaban biasanya berlangsung sekitar tiga generasi—kurang lebih satu abad. Pola ini bersifat berulang dan lintas peradaban.
Ibn Khaldun membagi masyarakat menjadi dua tipe utama: masyarakat nomaden (badawah) dan masyarakat sedentari perkotaan (hadarah).
Masyarakat nomaden hidup dalam kondisi keras dan penuh tantangan. Situasi ini menumbuhkan solidaritas kelompok (ashabiyah) yang kuat, keberanian, serta kemampuan adaptasi tinggi.
Ikatan kolektif tersebut memungkinkan mereka membangun kekuatan politik dan militer, bahkan menaklukkan masyarakat kota.
Sebaliknya, masyarakat perkotaan yang hidup menetap cenderung mengalami pelemahan solidaritas sosial. Kehidupan kota yang individualistik membuat warga mengandalkan institusi negara—polisi, birokrasi, aparat—untuk menjaga keamanan dan keteraturan.
Ketimpangan ekonomi, gaya hidup elit yang mewah, korupsi, serta meningkatnya kriminalitas melemahkan kohesi sosial.
Menurut Ibn Khaldun, kondisi inilah yang membuat masyarakat kota rentan ditaklukkan oleh kelompok dengan solidaritas sosial yang lebih kuat.
Ia menegaskan bahwa ashabiyah adalah kunci kejayaan peradaban. Ketika solidaritas sosial menguat, peradaban tumbuh. Namun ketika kemewahan, ketidakadilan, dan korupsi merajalela, solidaritas melemah dan kehancuran menjadi tak terelakkan.
Empat Fase Peradaban
Ibn Khaldun menjelaskan bahwa peradaban bergerak melalui empat fase utama. Fase pertama adalah fase perjuangan dan pembentukan.
Peradaban lahir dari kelompok dengan solidaritas kuat, semangat kolektif, dan komitmen bersama untuk bertahan dan berkembang. Nilai kesederhanaan, keberanian, dan pengorbanan menjadi fondasi utama.
Fase kedua adalah fase kejayaan. Stabilitas politik terbentuk, ekonomi berkembang, ilmu pengetahuan dan kebudayaan tumbuh subur, serta infrastruktur diperluas.
Pada tahap ini, masyarakat menikmati hasil kerja keras generasi sebelumnya. Solidaritas sosial masih ada, tetapi mulai melemah seiring meningkatnya kenyamanan hidup.
Fase ketiga adalah fase kemunduran. Generasi penerus lebih menikmati hasil daripada memperjuangkannya. Kemewahan meningkat, inovasi menurun, dan solidaritas sosial terkikis. Konflik internal, persaingan elite, serta ketidakadilan sosial mulai menguat.
Fase keempat adalah kehancuran. Ketika fondasi sosial, ekonomi, dan politik runtuh, peradaban tidak lagi mampu bertahan. Yang tersisa hanyalah jejak sejarah, sementara siklus baru dimulai oleh kelompok lain dengan solidaritas yang lebih kuat.
Bagaimana dengan Indonesia?
Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah ruang kosong peradaban. Sriwijaya dan Majapahit pernah tampil sebagai kekuatan besar yang menguasai jalur maritim, perdagangan, dan kebudayaan kawasan.
Namun kejayaan itu tidak bersifat abadi. Ketika solidaritas politik melemah, pusat kekuasaan terfragmentasi, dan kemampuan beradaptasi menurun, kedua peradaban tersebut runtuh dan digantikan oleh entitas-entitas yang lebih kecil.
Indonesia modern, yang dimulai sejak kemerdekaan 1945, kini sedang menapaki usia menuju satu abad pada 2045. Dalam perspektif Ibn Khaldun, usia ini merupakan fase kritis dalam siklus peradaban.
Pertanyaannya bukan sekadar seberapa lama Indonesia berdiri, tetapi pada tahap apa bangsa ini berada: apakah masih dalam fase membangun fondasi peradaban dengan visi kebangsaan yang kuat, atau justru mulai kehilangan momentum karena lemahnya solidaritas sosial dan kepemimpinan strategis.
Dalam bahasa ekonomi, kegelisahan itu terpantul dalam wacana middle income trap—kondisi ketika negara memiliki potensi besar, tetapi gagal melompat menjadi bangsa maju karena stagnasi inovasi, industrialisasi yang setengah matang, dan ketimpangan struktural yang tak terselesaikan.
Solidaritas Sosial sebagai Kunci
Ibn Khaldun menegaskan bahwa peradaban maju jika memiliki solidaritas sosial yang kuat. Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial besar melalui budaya gotong royong.
Di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, misalnya, tradisi berburu paus dilakukan secara kolektif—mulai dari persiapan hingga pembagian hasil—sebagai ekspresi solidaritas sosial yang hidup.
Émile Durkheim mengingatkan bahwa solidaritas sosial harus disertai collective effervescence, yakni rasa kebahagiaan dan keterikatan bersama. Jika masyarakat tidak merasa adil, aman, dan sejahtera, solidaritas akan rapuh.
Ibn Khaldun juga memperingatkan bahwa solidaritas sosial hancur oleh korupsi dan ketidakadilan. Ketika kekayaan menumpuk pada segelintir elite, sementara mayoritas masyarakat tertinggal, ashabiyah melemah. Kehidupan elite yang korup dan nepotistik mempercepat kehancuran peradaban.
Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Indeks persepsi korupsi yang stagnan menunjukkan bahwa ancaman terhadap solidaritas sosial belum teratasi sepenuhnya. Jika dibiarkan, ketidakadilan ekonomi akan semakin melebar dan melemahkan fondasi kebangsaan.
Demokrasi dan Masa Depan Peradaban
Bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi bukan sekadar pilihan sistem politik, melainkan prasyarat keberlanjutan peradaban.
Demokrasi menyediakan ruang bersama bagi kelompok yang berbeda—agama, etnis, kelas sosial—untuk hidup berdampingan tanpa saling meniadakan.
Melalui hak suara yang setara, setiap warga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kolektif bangsa, sekalipun pandangan dan kepentingan mereka beragam.
Di sinilah demokrasi bekerja sebagai mekanisme penyaluran konflik secara damai, mencegah ketegangan sosial berubah menjadi kekerasan dan perpecahan.
Lebih jauh, demokrasi menuntut akuntabilitas kekuasaan. Kekuasaan yang diawasi, dibatasi, dan dikoreksi secara terbuka memberi peluang lebih besar bagi lahirnya keadilan sosial.
Tanpa demokrasi yang substantif, solidaritas sosial mudah terkikis oleh ketimpangan, korupsi, dan dominasi kelompok tertentu. Bagi Indonesia, terutama para pemimpinnya, menjaga demokrasi berarti merawat fondasi peradaban itu sendiri.
Siklus peradaban memang keniscayaan sejarah, tetapi kehancuran bukanlah takdir yang tak terelakkan. Pertanyaannya kini: apakah demokrasi Indonesia akan sungguh menjadi energi pemersatu peradaban, atau justru berubah menjadi panggung perebutan kuasa yang mempercepat kemundurannya?